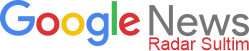RADAR SULTIM – Fatherless kian populer bukan karena itu sebuah prestasi, tapi itulah luka yang dirasakan jutaan anak Indonesia. Baru-baru ini media sosial diramaikan dengan tagar #fatherless, cerita anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran Ayah, baik secara fisik maupun psikis menuai ribuan simpati. Mereka berbagi luka yang sama : tumbuh di rumah yang lengkap secara struktur tapi kosong secara makna.
Ada yang kehilangan sosok Ayah karena Ayahnya telah meninggal dunia, ada yang ditelantarkan karena Ayahnya tidak bertanggungjawab, ada juga yang Ayah dan Ibunya telah bercerai sehingga mereka kehilangan sosok Ayah. Ada juga yang lengkap dalam rumah, tapi Ayah tidak berperan sebagai pemimpin dalam rumah, hanya sekedar memberi fasilitas mewah tanpa terlibat dalam pengasuhan dan perkembangan anak, uang mengalir tapi kehangatan mengering dan masih banyak lagi kisah pilu di baliknya.
Fatherless adalah kondisi anak yang tumbuh tanpa kehadiran figur Ayah, baik secara fisik maupun emosional. Kondisi ini bisa terjadi meskipun Ayah masih hidup. Penyebabnya beragam, termasuk perceraian atau perpisahan orangtua, kematian Ayah, ketidakhadiran fisik Ayah karena sibuk bekerja sehingga tak punya waktu lagi untuk membersamai dan mendidik anak dalam rumah. Dan faktanya sebanyak 20,1 persen atau 15,9 juta anak Indonesia berpotensi tumbuh “Fatherless” data ini berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Maret 2024. Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara Fatherless. Tentu saja ini berpengaruh pada perkembangan generasi bangsa di masa depan jika tidak segera diputus mata rantai “Fatherless” ini.
Dari konten Instagram @ruthhelga pada 17 Juli 2025. Hingga Senin (18/8/2025), konten tersebut sudah disukai 32.400 akun, dikirimkan 1.213 kali, serta memperoleh 959 komentar. Dari warganet yang mengalami muncul beberapa respon, pertama, ada yang ia tak merasakan peran Ayahnya meskipun tinggal seatap, ia menilai Ayahnya tidak dewasa, sehingga membuatnya tidak bermimpi untuk berumah tangga. Kedua, ada juga warganet yang menyatakan berhasil hidup layak, walaupun dulu ditelantarkan ayahnya. Sayangnya, hatinya masih kosong dan merasa tidak punya tempat pulang, dia juga tidak tau harus bertanya kepada siapa apabila kebingungan melanda.
Menurut laporan Kompas.id (14/10/2025), jutaan anak di Indonesia kini mengalami kondisi fatherless, yaitu ketiadaan peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Kondisi ini bukan hanya akibat perceraian atau kematian, tetapi karena banyak ayah yang “hilang” di tengah kesibukan dunia kerja.
Fakta serupa diungkap Kompas.id (12/10/2025), bahwa dukungan terhadap anak-anak Fatherless kini mengalir deras lewat media sosial. Para ibu tunggal, konselor keluarga, hingga influencer ramai membicarakan isu ini, dengan narasi penyembuhan luka batin dan penguatan peran Ibu.
Lalu bagaimana menurut para ahli terkait Fatherless? Dari hasil survei kualitatif pada 16 psikolog klinis di 16 kota di Indonesia, dampak Fatherless yang terjadi bisa berupa rasa minder dan emosi/mental yang labil. Ini disebut masing-masing oleh sembilan psikolog. Adapun tujuh psikolog menjawab kenakalan remaja. Lima psikolog menyebut sulit berinteraksi sosial dan empat menjawab motivasi akademik rendah sebagai dampak berikutnya.
Ada pengaruh yang kuat antara jumlah anak berpotensi fatherless dan jumlah anak bermasalah dengan hukum, dengan angka korelasi regresi 0,72 poin. Anak yang kehilangan figur ayah cenderung memiliki tingkat stres lebih tinggi, risiko kenakalan remaja, serta kesulitan dalam membangun kepercayaan diri dan identitas yang sehat.
Tentu saja, dari fakta dan data diatas, Fatherless tidak lahir dari ruang hampa, tapi buah sistem kapitalisme sekuler. Fenomena Fatherless lahir dari rahim peradaban kapitalistik-sekuler yang menuhankan materi dan menyingkirkan nilai-nilai ilahi. Dalam sistem ini, manusia diukur dari seberapa besar ia berkontribusi pada roda perekonomian, bukan seberapa utuh ia menjalankan fitrahnya. Desakan ekonomi memaksa para Ayah bekerja tanpa henti. Dari pagi hingga larut malam, waktu habis untuk mengejar angka di slip gaji. Rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat mendidik. Sehingga tak punya waktu untuk ikut andil dalam tumbuh kembang anak. Akhirnya, anak-anak kehilangan figur teladan yang mencontohkan kekuatan iman, tanggung jawab dan rasa aman.
Kembali ke data yang dirilis Kompas. Dari 15,9 juta anak yang tumbuh Fatherless, 4,4 juta di antaranya tinggal di keluarga tanpa Ayah. Tapi yang mengejutkan, angka lebih besar, yaitu 11,5 juta anak, sebenarnya tinggal bersama Ayah yang memiliki jam kerja lebih dari 60 jam per pekan atau lebih dari 12 jam per hari. Artinya, seorang Ayah lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah daripada bertemu anak di rumah. Padahal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebut jam kerja formal maksimal tujuh jam per hari atau 40 jam per minggu. Ayah berangkat kerja subuh ketika anak-anak belum bangun, dan Ayah pulang tengah malam sehingga anak-anak sudah tertidur. Sehingga tidak sinkron waktu antara ayah dan anak.
Dalam sistem sekuler yang menyingkirkan agama dari kehidupan, peran Ayah direduksi menjadi sekadar “pencari uang.” Ia bukan lagi qawwam yang menuntun keluarga dengan nilai akidah, melainkan penyedia kebutuhan materi. Maka tak heran, banyak anak kehilangan arah, mencari figur di luar rumah, bahkan menghabiskan waktu di depan layar ponsel untuk mencurahkan lukanya.
Kapitalisme menanamkan logika bahwa keberhasilan laki-laki diukur dari karir dan penghasilan. Sementara perempuan didorong untuk “setara” di ranah publik, meski harus mengorbankan anak di rumah. Akhirnya, keluarga kehilangan keseimbangan. Fungsi pengasuhan, pendidikan, dan pembinaan spiritual diserahkan kepada sekolah, pengasuh, bahkan media sosial.
Padahal, Islam menempatkan Ayah sebagai figur sentral dalam pendidikan anak. Kisah Luqman al-Hakim menjadi teladan, bagaimana seorang Ayah menanamkan tauhid dan akhlak pada anaknya dengan hikmah. Ayah bukan sekadar pemberi nafkah, tapi penjaga aqidah dan pembentuk karakter. Namun, dalam sistem sekuler, peran spiritual itu tercerabut. Negara tak menjamin kehidupan keluarga secara adil. Lapangan kerja terbatas, upah rendah, biaya hidup tinggi. Akibatnya, Ayah bekerja keras bukan untuk mendidik, tapi sekadar bertahan hidup.
Berbeda halnya dengan Islam yang menjaga fungsi Ayah dan menjamin kehidupan, Dalam pandangan Islam, Ayah adalah qawwam—pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab keluarga. Fungsinya bukan hanya memberi nafkah, tetapi menegakkan syariat Allah dalam rumah tangganya. Ia mendidik dengan iman, membimbing dengan kasih, dan menuntun dengan akhlak.
“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (TQS An-Nisa:34)
Ayat ini menegaskan peran laki-laki sebagai qawwam (penanggung jawab dan pelindung) keluarga. Dalam Islam, qawwamah bukan sekadar status, tapi amanah ilahiah untuk memimpin dengan syariat.
Negara dalam sistem Islam juga tidak membiarkan ayah berjuang sendirian. Ia wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat: pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dengan demikian, Ayah dapat menjalankan perannya tanpa tercekik tekanan ekonomi.
Sistem Islam pun memiliki mekanisme perwalian yang memastikan setiap anak—bahkan yatim sekalipun—tetap memiliki figur pembimbing dan pelindung. Tidak ada istilah anak kehilangan sosok Ayah, karena masyarakat Islam hidup dalam sistem yang berlandaskan tanggung jawab kolektif dan solidaritas keimanan. Isu Fatherless tidak bisa diselesaikan hanya dengan kampanye “hadir untuk anak.” Selama sistem yang membuat Ayah tersita waktu tidak diubah, luka ini hanya akan berulang.
Kita harus berani menatap akar masalahnya: sekularisme telah melahirkan peradaban yang kering dari nilai ilahi, yang menjauhkan manusia dari peran fitrahnya. Selama kapitalisme menjadi panglima, Ayah akan terus teralienasi, dan anak-anak akan tumbuh tanpa pelindung spiritual.
Islam akan menempatkan keluarga sebagai pusat peradaban, maka Ayah akan kembali pada fitrahnya — sebagai qawwam, pelindung, dan pendidik sejati.