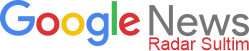RADAR SULTIM – Isu degradasi hutan di Indonesia adalah paradoks yang menyakitkan. Negara kita, yang dianugerahi kekayaan hutan tropis terbesar kedua di dunia, justru tercatat sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar akibat deforestasi. Krisis ini bukan sekadar kegagalan menjaga lingkungan, melainkan sebuah kegagalan sistemik yang berakar pada konsep tata kelola hutan yang berorientasi pada pasar bebas atau kapitalisme. Ketika pertumbuhan ekonomi dijadikan kiblat utama, hutan pun direduksi fungsinya, dari penyangga kehidupan menjadi sekadar komoditas yang dijual-beli melalui mekanisme perizinan konsesi.
Data dari kurun waktu 2000-2010 menunjukkan betapa dominannya peran industri dalam kehancuran ekosistem. Industri penebangan, perkebunan serat, dan kelapa sawit secara kolektif menyumbang hampir setengah (44,7%) dari kehilangan hutan di pulau-pulau utama. Walaupun kelapa sawit menempati urutan ketiga dalam luas lahan yang dikonversi, ia menjadi penyumbang emisi karbon tertinggi kedua, menunjukkan intensitas kerusakan yang disebabkannya.
Mekanisme legal yang memfasilitasi kerusakan ini adalah Hak Konsesi. Melalui perizinan dari pemerintah, pihak swasta—baik korporasi domestik maupun multinasional—diberi hak istimewa untuk membuka dan mengelola (baca: mengeksploitasi) lahan hutan. Desentralisasi kebijakan (PP No. 38 tahun 2007) dan kewenangan penuh pemerintah pusat (UU No. 23 tahun 2014) dalam penerbitan izin konsesi menjadikan pemerintah sebagai aktor sentral yang memegang kendali atas nasib hutan.
Logika yang melanggengkan deforestasi adalah asumsi bahwa pembukaan hutan diperlukan demi memenuhi kebutuhan produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Argumen ini sesungguhnya adalah justifikasi bagi tata kelola hutan yang didominasi oleh ideologi kapitalis.
Kapitalisme mengusung pasar bebas, di mana modal diizinkan bergerak bebas menuju tempat yang paling menguntungkan. Dalam konteks kehutanan, hal ini diterjemahkan menjadi: semakin kecil biaya produksi, semakin besar keuntungan. Prinsip inilah yang seringkali membuat korporasi memilih teknik pembukaan lahan yang merusak, termasuk pembakaran (land clearing), karena modalnya kecil namun hasilnya maksimal.
Akibatnya, negara Indonesia terjerat dalam dilema yang merugikan:
- Kepentingan Kapitalis di Atas Rakyat: Sistem hukum agraria Indonesia masih mengakar pada doktrin liberalisme, yang melegalkan alih fungsi hutan untuk pembangunan, namun pada kenyataannya hanya menguntungkan kelompok kapitalis (fragmentary group), bukan kesejahteraan rakyat luas.
- Menanggung Beban Ekologis (Ecological Cost): Negara kehilangan daya tekan di hadapan pemegang konsesi. Di satu sisi, negara harus menanggung beban finansial dan moral atas bencana ekologis (banjir, longsor, intrusi air laut) dan polusi lintas batas (Karhutla). Di sisi lain, negara terus dituntut oleh tekanan internasional untuk menjaga iklim global.
- Fungsi Negara Terdistorsi: Negara hanya berposisi sebagai regulator atau fasilitator bagi pasar, bukan sebagai pengatur dan pengelola penuh sumber daya alam yang seharusnya untuk kemaslahatan rakyat. Inilah yang membuat berbagai kebijakan pengendalian deforestasi menjadi tidak efektif, bahkan terkesan hanya bersifat propagandis.
Jika ambisi Indonesia untuk menekan laju deforestasi dan melestarikan lingkungan itu sungguh-sungguh, maka ketergantungan pada investasi pihak ketiga (swasta) yang berorientasi pasar harus diakhiri. Kita harus berani mengambil langkah berani untuk mereformasi sistem tata kelola hutan:
Pertama, Hutan Harus Dikelola sebagai Kepemilikan Umum. Negara harus menghentikan konsep konsesi dan mengambil alih fungsi pengelolaan hutan secara penuh. Sumber daya alam adalah milik negara dan harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat secara lestari. Kedua, Negara Harus Menjadi Pengelola, Bukan Sekadar Fasilitator. Dengan mengelola penuh, negara dapat menyeimbangkan tiga pilar utama: kepentingan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian ekologis. Hal ini mencakup investasi dalam teknologi terkini untuk pencegahan kerusakan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Mempertahankan tata kelola berbasis kapitalisme sama saja dengan membiarkan kerusakan lingkungan terus-menerus terjadi, menukar hutan dengan segelintir materi, dan membahayakan keberlangsungan negara itu sendiri. Sudah waktunya Indonesia mandiri dalam mengolah sumber daya alam, lepas dari pengaruh pasar, demi menjamin warisan ekologis untuk generasi mendatang.